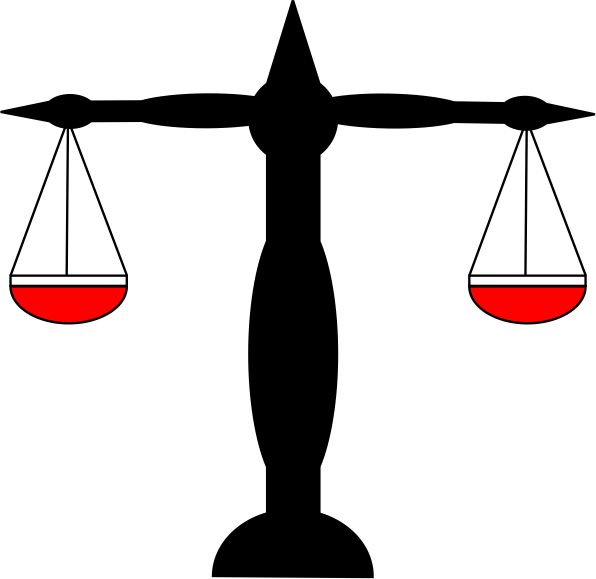Oleh : Everd Utubira
Dalam dinamika pendidikan modern, pendekatan pedagogis sering kali diwarnai oleh sistem dan nilai-nilai yang tidak sepenuhnya mencerminkan kekayaan budaya lokal. Hal ini berpotensi menciptakan distance antara peserta didik dengan realitas sosial dan budaya mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan pendekatan pendidikan yang tidak hanya bersifat transformatif, tetapi juga kontekstual dan membumi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pedagogi pembebasan yang diperkenalkan oleh Paulo Freire, seorang tokoh pendidikan kritis yang menekankan pentingnya kesadaran reflektif, dialog, dan pembebasan dari penindasan struktural.
Dalam konteks lokal Masyarakat Halmahera secara khusus masyarakat Halmahera Utara dengan latar kultur Tobelo-Galela (TOGALE), konsep Hibualamo sebagai rumah adat tradisional masyarakat Halmahera menjadi simbol penting dari nilai-nilai kolektivitas, musyawarah, dan harmoni sosial. Hibualamo bukan sekadar bangunan fisik, melainkan representasi dari sistem nilai dan identitas budaya masyarakat. Jika dibaca melalui lensa pedagogi Freire, Hibualamo dapat dipahami sebagai ruang dialogis yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan yang membebaskan, di mana masyarakat menjadi subjek aktif dalam membentuk kesadaran dan menentukan arah hidup mereka sendiri. Melalui pembacaan budaya lokal seperti Hibualamo dengan pendekatan pedagogi pembebasan, pendidikan dapat menjadi alat pemberdayaan yang tidak terlepas dari akar budaya masyarakat. Pendekatan ini mendorong lahirnya pendidikan yang tidak hanya mendidik secara intelektual, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis dan solidaritas sosial.
Hibualamo diartikan sebagai “Rumah Besar” yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai elemen masyarakat. Lebih dari sekadar bangunan fisik, Hibualamo mencerminkan struktur sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat Halmahera yang mengedepankan kolektivitas, dialog, dan keberagaman. Dalam struktur dan tata ruangnya, Hibualamo dirancang untuk mendukung interaksi dan partisipasi bersama, menjadikannya sebagai wadah penting dalam pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh elemen komunitas. Sebagai ruang simbolik, Hibualamo juga memiliki makna spiritual dan identitas yang kuat. Ia menjadi titik temu antara masa lalu dan masa kini, antara nilai-nilai adat dan tantangan modernitas. Di dalamnya terkandung nilai-nilai gotong royong, solidaritas sosial, kesetaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Semuanya merupakan landasan penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis.
Dalam perspektif pendidikan, konsep Hibualamo dapat dimaknai sebagai bentuk lokal dari ruang edukatif yang dialogis. Ini sejalan dengan prinsip pedagogi pembebasan ala Freire, yang menempatkan ruang pendidikan sebagai arena pembentukan kesadaran kritis dan tindakan kolektif. Hibualamo, dengan semangat keterbukaannya, menjadi cerminan lokal dari model pendidikan yang tidak hierarkis, melainkan kolaboratif dan partisipatif. Dengan demikian, memahami Hibualamo berarti memahami cara masyarakat Halmahera membangun relasi sosial yang egaliter dan dialogis, yang relevan untuk dikontekstualisasikan dalam proses pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan.
Ricardo Nanuru menjelaskan, terminologi nilai, baik dari perspektif sejarah, antropologi maupun sosiologi sama dipahami sebagai ukuran tentang baik buruk serta benar salah. Kedudukan nilai pada setiap kebudayaan sangatlah penting, dimana nilai budaya terdiri dari ide, gagasan maupun konsepsi. Budaya lokal Hibualamo tidak hanya merepresentasikan identitas etnik masyarakat Halmahera, tetapi juga menjadi cermin dari sistem nilai yang berorientasi pada kebersamaan, musyawarah, dan kesetaraan sosial. Dalam konteks sosiokultural, Hibualamo merupakan institusi tradisional yang merekatkan berbagai kelompok masyarakat dalam satu ruang bersama, tanpa batas-batas eksklusif berdasarkan agama, suku, atau status sosial. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Halmahera secara historis telah memiliki sistem sosial yang inklusif dan demokratis. Dari segi nilai, Hibualamo memuat prinsip-prinsip yang sangat relevan dengan semangat pedagogi pembebasan Paulo Freire, seperti partiispasi, kesetaraan, identitas dan pembebasan kultural, hingga resistensi kultural dan ketahanan sosial.
Paulo Freire, tokoh utama dalam pemikiran pedagogi pembebasan, menawarkan pendekatan pendidikan yang menempatkan manusia sebagai subjek aktif dalam proses belajar, bukan sekadar objek pasif yang dijejali informasi. Ia menolak sistem pendidikan Gaya Bank, dimana pendidik menjadi satu-satunya sumber pengetahuan dan murid hanya berperan sebagai penyimpan informasi. Sebagai gantinya, Freire mendorong pendidikan yang dialogis, kontekstual, dan berbasis pada realitas kehidupan peserta didik. Jika pendekatan Freire ini dibaca dalam konteks budaya lokal seperti Hibualamo, maka sejumlah prinsip kunci pedagogi pembebasan dapat diterapkan secara nyata mulai dari dialog sebagai metode pendidikan, pembentukan kesadaran kritis dan transformasi sosial berbasis budaya. Penerapan teori Paulo Freire dalam konteks Hibualamo menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki potensi besar untuk mendukung praktik pendidikan yang membebaskan. Dengan menjadikan Hibualamo sebagai ruang belajar yang alami dan sarat makna, pendidikan dapat keluar dari kerangka yang kaku dan menjadi proses yang dialogis, membumi, serta transformatif. Ini adalah wujud nyata dari pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga memanusiakan dan memberdayakan.
Relevansi Hibualamo dalam Pendidikan Kritis Paulo Freire
Dalam konteks pendidikan modern yang semakin distandarisasi dan global, nilai budaya lokal sering kali terpinggirkan. Pendidikan cenderung menjadi proses yang formal dan jauh dari kehidupan nyata peserta didik. Di sinilah pentingnya menghadirkan pendekatan yang berangkat dari konteks lokal dan kehidupan masyarakat, seperti yang ditawarkan oleh Paulo Freire melalui konsep pendidikan kritis. Dalam pendekatan ini, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer pengetahuan, melainkan sebagai proses dialogis yang membangun kesadaran kritis dan memberdayakan peserta didik untuk mengenali serta mengubah realitas sosialnya. Dalam kerangka tersebut, Hibualamo, sebagai simbol budaya masyarakat Halmahera, memiliki relevansi yang sangat kuat. Hibualamo bukan sekadar rumah adat secara fisik, melainkan juga ruang sosial dan simbol persatuan antar masyarakat yang berbeda latar belakang. Di dalam Hibualamo, masyarakat berkumpul untuk berdialog, bermusyawarah, dan menyelesaikan persoalan bersama secara egaliter. Nilai-nilai inilah yang sejalan dengan prinsip utama pendidikan kritis Freire, yakni pendidikan sebagai praktik pembebasan yang dimulai dari dialog dan keterlibatan aktif semua pihak.
Relevansi pertama dapat dilihat dari nilai dialogis yang melekat dalam budaya Hibualamo. Freire menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis pada dialog, di mana pendidik dan peserta didik saling belajar dan membangun pemahaman bersama. Dalam Hibualamo, semua orang memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan bersama. Dialog yang hidup dalam Hibualamo menjadi model ideal bagi praktik pendidikan yang demokratis dan partisipatif, bukan relasi satu arah yang menempatkan peserta didik sebagai objek pasif. Selain itu, Hibualamo merepresentasikan pendidikan yang kontekstual dan membumi, sebuah prinsip penting dalam pedagogi Freire. Pendidikan harus berangkat dari realitas kehidupan peserta didik, bukan dari kurikulum yang asing dan tidak relevan dengan keseharian mereka. Melalui Hibualamo, nilai-nilai lokal seperti gotong royong, solidaritas, keadilan, dan penyelesaian konflik secara damai bisa diangkat sebagai bahan ajar yang bermakna. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya belajar secara intelektual, tetapi juga mengalami proses pembelajaran yang menyentuh sisi kemanusiaan dan keberbudayaan mereka. Lebih jauh, Hibualamo juga menjadi ruang pembentukan kesadaran kritis. Freire menekankan pentingnya conscientização, yakni proses di mana individu mulai menyadari struktur ketidakadilan yang mengikatnya, dan terdorong untuk melakukan perubahan sosial. Melalui musyawarah di dalam Hibualamo, masyarakat tidak hanya berdialog, tetapi juga merefleksikan kondisi sosial, merumuskan masalah bersama, dan mencari solusi secara kolektif. Proses ini mencerminkan tujuan pendidikan kritis yang membentuk individu sadar sosial dan aktif dalam menciptakan perubahan. Terakhir, Hibualamo memiliki nilai strategis dalam memperkuat identitas budaya dan kemandirian komunitas. Dalam dunia yang didominasi oleh budaya global dan sistem pendidikan yang sering kali menjauhkan peserta didik dari akar budayanya, Hibualamo menjadi simbol penting dari pendidikan yang berbasis pada emansipasi budaya. Sejalan dengan pemikiran Freire, pendidikan yang membebaskan tidak boleh mengasingkan peserta didik dari budayanya sendiri, tetapi justru harus membangun kembali kebanggaan dan keberdayaan melalui warisan budaya yang dimiliki. Hibualamo menjadi bukti bahwa pendidikan dapat berlangsung secara autentik, tanpa kehilangan identitas lokal.
Dengan demikian, Hibualamo tidak hanya relevan sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai wujud nyata praktik pendidikan kritis yang membebaskan. Ia menghadirkan ruang belajar yang demokratis, dialogis, kontekstual, dan membumi. Dalam Hibualamo, kita menemukan bahwa pendidikan dapat tumbuh dari akar budaya sendiri, dan dari sanalah lahir kesadaran, keberanian, dan harapan untuk perubahan sosial yang lebih adil dan manusiawi.