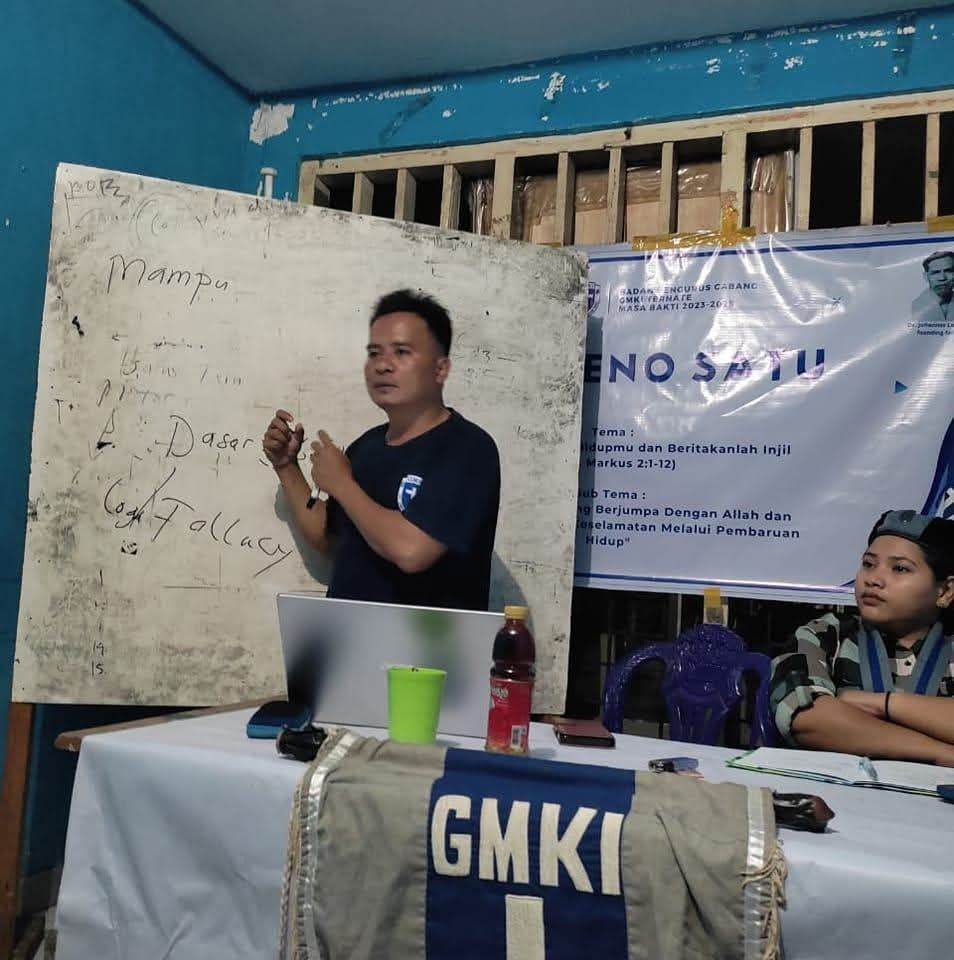
Oleh : John Sipondak (Mantan ketua GMKI Ternate)
Dalam sepekan ini ini publik Halmahera Selatan dihujani berita oleh media mainstream yang berseliweran didunia maya. Dimana focus tema yang jadi hangat perdebatan dialektika public dari berbagai kalangan bermunculan dalam memandang satu momen pelantikan 4 kades di Halmahera Selatan yang dinilai cacat hukum yang merupakan sumber utama sebagai landasan pijak parah pegiat media-media online dalam meluapkan tulisannya. Pada situasi itu datang satu berita yang cukup mencengangkan pembaca ketika salah satu advocad yang juga ikut mengomentari dengan menggunakan analogi bahwa pelantikan yang dilakukan seperti “nabi Isa membangkitkan orang mati” yang juga sebagai pemantik dan penyulut dalam beberapa pandangan terutama datang dari beberapa kalangan. Dalam mengartikulasikan beberapa pandangan itu saya juga ikut serta dalam mengemukakakan pandangan saya lewat opini kali ini, tetapi sebelumnya saya harus diskleimer dulu bahwa Opini itu : Obrolan Penting Hari Ini. Maka mari kita mengobrol dalam area kehebohan akibat analogi, yang akan saya ulas dalam beberapa segmen.
Analogi dalam ilmu filsafat bahasa
Dalam aliran ilmu filsafat khsusunya ilmu epistemology, analogi dan logika memiliki pandangannya masing-masing namun titik temu yang bisa mengeksplorasi berbagai ide untuk dikembangkan. Karena itu Analogi merupakan metode penalaran yang membandingkan dua hal berbeda berdasarkan keserupaan untuk menarik kesimpulan atau menjelaskan suatu ide yang kompleks. Yang dalam filsafat, hal ini bersifat induktif, di mana kesimpulan tidak mutlak tapi probabilistic. Fungsi Analogi sangat efektif untuk komunikasi ide abstrak, tetapi rentan terhadap kesalahan jika keserupaan dilebih-lebihkan (false analogy). oleh karenya John Locke dan David Hume, menekankan pentingnya pengujian melalui percobaan dan data konkret, menjadi dasar metode ilmiah modern di mana klaim harus diverifikasi secara empiris. Jika Analogi menghasilkan hipotesis (induktif-empiris), deduktif membangun model logis, dan empiris memverifikasi. Kita ambil missal dalam filsafat hukum, empirisme menguji analogi kasus hukum melalui bukti, sementara deduktif menerapkan prinsip umum. prinsip analogi dalam penalaran beberapa aliran seperti paham positivisme logis menggabungkan deduktif untuk struktur dan empiris untuk isi, dengan analogi sebagai alat komunikasi . karena itu ada wilayah Batasannya dalam memahami analogi subjektif, empiris terbatas pada yang teramati, dan deduktif bergantung pada premis akurat maka integrasi diperlukan untuk menghindari reduksionisme.
Analogi dalam Filsafat Bahasa merupakan konsep sentral dalam filsafat bahasa, yang didefinisikan sebagai persamaan atau kesesuaian antara dua hal atau benda yang berbeda, sering digunakan untuk menjelaskan ide-ide kompleks melalui perbandingan. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Yunani “analogos”, yang berarti “proporsional” atau “sebanding”, dengan akar pada “logos” yang menyiratkan rasio atau alasan. Dalam filsafat bahasa, analogi bukan sekadar alat retoris, melainkan proses penalaran yang menghubungkan bahasa dengan pemikiran filosofis. Dalam ilmu psikolinguistik analogi dipandang sebagai gaya berbahasa yang tampak (seperti berbicara atau menulis) dan tidak tampak (seperti persepsi atau pemahaman), termasuk bagaimana struktur bahasa diperoleh dan digunakan dalam komunikasi . Pandangan ini menekankan bahwa bahasa bukan proses mekanis semata, melainkan dipengaruhi oleh pikiran manusia, seperti resepsi, persepsi, dan produksi bahasa. Analogi dalam konteks ini merujuk pada penalaran induktif yang membandingkan kesamaan antara dua hal untuk memahami konsep baru atau kompleks. Analogi bukan sekadar perbandingan sederhana, melainkan alat kognitif untuk meramalkan kesamaan, mengungkap kekeliruan, atau membangun klasifikasi, sering digunakan dalam pembelajaran bahasa untuk menyederhanakan ide abstrak.
Dialektika Dogma agama-agama.
Beberapa mahakrya warisan pemikiran-pemikiran yang sudah ditinggalkan untuk menjadi ide penuntun kita dalam memahami realitas kekinian misalnya buku karya Al-Ghazali tentang Sciences of Religion terutama dalam pembahssan tentang kenabian dan mukjizat, nabi Isa sebagai teladan spiritual dan rasul tauhid. Al-Ghazali mengintegrasikan kisah Isa dari Al-Qur’an dengan sufisme, menekankan aspek ruhani beliau sebagai “tabib jiwa” yang menyembuhkan penyakit hati umat. Al-Ghazali berargumen bahwa mukjizat Isa (seperti menghidupkan mati dan berbicara sebagai bayi) bukan bukti keilahian, melainkan tanda kekuasaan Allah yang menegaskan kewajiban iman. Ia menolak doktrin Kristen tentang Trinitas sebagai bentuk syirik, dengan Isa sebagai saksi utama tauhid: “Isa adalah hamba Allah, bukan anak-Nya Isa melambangkan fana’ (peleburan diri dalam Allah) dan zuhud (kepolosan duniawi), di mana beliau hidup tanpa harta atau istri untuk fokus pada ibadah. Ini mendukung doktrin bahwa semua nabi adalah “muslim” (penyerah diri kepada Allah).
Dalam pandangan M. Quraish Shihab (Edisi Modern, 2000-an) Tafsiran kontemporer ini menganalisis ayat-ayat tentang Isa di surah seperti Ali Imran dan Maryam, dengan pendekatan kontekstual yang menggabungkan doktrin, filsafat, dan sejarah. Shihab menekankan Isa sebagai simbol dialog antara gama sambil mempertahankan akidah Islam. Argumen sentral adalah bahwa pengangkatan Isa ke langit membuktikan keadilan ilahi, menghindari penyaliban sebagai hukuman tidak adil. Ini menyanggah narasi Kristen sebagai “penebusan dosa”, dengan penekanan bahwa dosa adalah tanggung jawab pribadi, bukan warisan (kontras dengan dosa asal Adam).
Dalam sebuah Buku Filsafat Ilmu dan Logika yang ditulis oleh Prof. Dr. Waston, M.Hum. merupakan panduan komprehensif yang mengintegrasikan filsafat ilmu dengan logika, menekankan perlunya jembatan antara pemikiran rasional dan nilai kemanusiaan. Waston mendefinisikan analogi sebagai bentuk penalaran logis yang membandingkan dua hal berbeda untuk menarik kesimpulan proporsional, bukan identik. Analogi bukan sekadar metafor retoris, melainkan fondasi ontologis dan epistemologis dalam filsafat, di mana kesamaan struktural (seperti hubungan sebab-akibat) digunakan untuk menjelaskan yang tidak terlihat dari yang terlihat. Ini mencerminkan genealogi analogi dari Aristoteles sebagai “proportion” dalam Metafisika hingga pemikir modern, di mana analogi menghindari reduksionisme materialis dengan mengakui batas pengetahuan manusia. Pada Abad Pertengahan Thomas Aquinas’ menulis Summa Theologica, yang menggunakan analogi entis untuk hubungan Tuhan-ciptaan. Menurut Waston, analogi adalah jembatan antara signifier (bentuk bahasa) dan signified (makna), mirip juga dengan Saussure. Yang menganalogikan evolusi makna kata dengan adaptasi biologis, di mana konteks empiris (bukti deduktif) membentuk interpretasi, relevan untuk analisis teks agama komparatif. Waston juga menekankan risiko analogi jika berlebihan, ia menjadi fallacy (kesalahan logis), seperti false analogy dalam debat filsafat. Namun, sebagai alat, analogi memperkaya deduksi dengan bukti empiris, seperti dalam filsafat sains modern. filsafat melayani teologi tanpa mendominasi. Ia merujuk dialektika filsafat-teologi, di mana analogi menjembatani yang transenden (Tuhan) dengan imanen (dunia ciptaan). Pada Abad Pertengahan, filsafat sering tunduk pada teologi (seperti Aquinas yang menggunakan analogi untuk membuktikan eksistensi Tuhan via (via analogiae), sementara Renaisans memisahkan keduanya akibat individualisme dan kritik terhadap dogmatisme gereja. Waston menekankan analogi sebagai alat dialog, mengurangi konflik dengan menyoroti kesamaan esensial misalnya, rahmat ilahi dalam mukjizat Isa, sambil menghormati perbedaan. Ini mendukung teologi kerukunan, di mana filsafat bahasa membangun pemahaman bersama. Seiring dengan hal itu Agama, Keterbukaan, dan Demokrasi: Harapan dan Tantangan yang ditulis oleh Franz Magnis Suseno Sebagai filsuf Katolik Jesuit yang telah lama berkontribusi dalam pemikiran etika dan dialog antar agama di Indonesia, Magnis-Suseno mengeksplorasi hubungan dinamis antara agama, keterbukaan dan demokrasi. Ia menekankan bahwa iman sejati harus melahirkan hormat terhadap sesama manusia, terutama di tengah tantangan kontemporer seperti ekstrem agamaan dan budaya konsumerisme kapitalistik.
Kiblat Politik
Apakah ada bursa efek pengaruh Perbedaan Kiblat Politik terhadap Kehidupan Bersama jika merujuk pada arah atau orientasi ideologi politik suatu kelompok, partai, atau individu, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor seperti agama, etnis, atau kepentingan ekonomi dapat membentuk dinamika sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Emile Durkheim menekankan masyarakat sebagai realitas objektif dari interaksi anggotanya, yang bisa terganggu oleh perbedaan eksternal.
Pengaruh Perbedaan Kiblat Politik
Perbedaan kiblat politik sering memicu konflik yang merusak kehidupan bersama. Ambil misal yang kompleks di Indonesia, politik identitas seperti yang berbasis agama atau etnis dapat mempertegas perbedaan, menyebabkan diskriminasi, kekerasan, dan ketidakstabilan sosial. Fenomena populisme berafiliasi dengan identitas agama budaya juga berpotensi menggiring masyarakat ke polarisasi, mengancam integritasi dan kebersamaan. Selain itu, lemahnya partai politik akibat kiblat yang tidak konsisten menyebabkan janji kampanye tak terpenuhi, membangun pesimisme masyarakat terhadap institusi demokrasi, dan mengurangi partisipasi politik yang sehat. Media massa pun ikut memperburuknya dengan bias ideologi, memengaruhi perilaku politik masyarakat melalui framing berita yang tidak netral. Dalam konteks local. Meski dominan negatif, perbedaan kiblat politik bisa mendorong dialog dan inovasi jika dikelola secara baik. Di era dunia digital dapat memengaruhi norma sosial, mendorong individualisme yang melemahkan kebersamaan.
Peran Harmoni Antar-Umat Beragama sebagai Jembatan
Harmoni antar-umat beragama dapat menjadi jembatan krusial untuk mengatasi efek kiblat politik, terutama melalui pemikiran Nurcholish Madjid (Cak Nur), seorang pemikir Islam moderat yang menekankan pluralisme dan toleransi. Madjid menggagas pluralisme agama sebagai sikap lapang dada dan terbuka, di mana dialog antar-umat bertujuan menciptakan hubungan harmonis dengan mencari titik temu, bukan perbedaan. Ia berpendapat bahwa kerukunan antar-umat beragama diasumsikan melalui diskusi asas toleransi, di mana tauhid sebagai tujuan utama mendorong kesadaran dialogis dan civil society yang kuat, selaras dengan kemajemukan. Dia juga memperkenalkan konsep titik persamaan antar-agama, membangun harmoni yang mendukung demokrasi inklusif dimana toleransi menjadi solusi untuk masyarakat majemuk, mencegah kiblat politik berbasis identitas yang dapat merusak kebersamaan dengan demikian, menjaga harmoniasi yang sudah terbangun ini bisa menjembatani perbedaan kiblat politik, memperkuat demokrasi melalui dialog yang menghargai kemajemukan. Secara keseluruhan, kiblat politik berpotensi melemahkan demokrasi melalui polarisasi, tapi harmoni antar-umat beragama menawarkan jalan keluar dengan membangun toleransi dan pluralisme sebagai fondasi kehidupan bersama.








